Malam ini, sepulang dari sebuah kota yang masih menjadi favorit saya. Meski kini kota itu tak lagi sedingin dulu, juga sudah hampir semacet Surabaya. Begitu keluhan yang saya dengar dari segelintir orang yang telah lama bermukim di sana.
Kota ini menjadi favorit, bukan saja karena saya sempat lahir dan tinggal di sana selama beberapa tahun. Tapi kota ini juga menyimpan banyak kenangan, terutama tentang masa kecil dan beberapa momen yang pernah terlewati dangan sejumlah teman lama.
♯
Kali ini saya menyambangi kota itu bertiga saja dengan Ayah dan Ibu. Setelah saya menyelesaikan sebuah urusan di kampus selama hampir dua jam, Ayah menyempatkan diri mampir ke rumah temannya yang tak jauh dari kampus saya.
Langit sudah berubah warna—perpaduan jingga, hitam, biru pucat, dan abu-abu saat Ayah menyudahi kunjungannya. Segera kami mencari masjid terdekat demi menunaikan Maghrib.
Kemudian, mobil kembali melaju lambat-lambat. Jalanan kota sedang padat, karena hari ini sudah masuk akhir pekan bagi sebagian orang. Senyum saya tak lelah melebar saat memandangi tiap sudut kota ini. Teringat, dulu saya pernah menyeberangi jalanannya, sempat menumpang angkutan umum khasnya yang berwarna biru itu, sempat pula menghabiskan malam dengan rangkaian cerita bersama beberapa teman lama di salah satu taman yang dimilikinya.
Ah, sudah berapa tahun berlalu, tapi kenangan itu masih tetap lekat dalam benak. Saya rindu saat seperti itu lagi.
Panggilan Ayah membuyarkan lamunan saya. Oh, rupanya mobil telah berhenti di depan sebuah mall. Semangat saya langsung naik dua kali lipat. Buru-buru saya keluar dari mobil, disusul Ibu. Sementara Ayah memarkirkan mobil di basement. Segera saya memasuki mall itu bersama Ibu. Tanpa mengulur waktu lagi, saya langsung menuju satu tempat yang selalu menjadi salah satu destinasi utama saya saat berkunjung ke sini. Sementara Ibu memilih berkeliling saja.
♯
Maka di sinilah saya sekarang. Berdiri diantara deretan rak buku dengan setengah takjub. Ah, betapa saya merindukan tempat ini, sama seperti saya merindukan kota ini. Beberapa kali saya mengitari rak-rak buku, dan memandang sekilas-kilas pada setiap judul buku yang tertata rapi di sana. Sejenak saya resah. Di mana buku yang saya cari, yang sudah lama membuat saya penasaran itu?
Maka, saya memutuskan berkeliling lagi. Dan ini dia! Inilah buku yang saya cari dan sekian lama membuat saya penasaran akan isinya.
Pertama, Cantik itu Luka, karya Eka Kurniawan. Saya pernah membaca artikel tentang penulis ini, sekaligus ulasan bukunya di koran Jawa Pos beberapa waktu lalu.
Kedua, sebuah buku kumpulan puisi karya Aan Mansyur, Tidak Ada New York Hari Ini. Saya mulai penasaran dengan nama Aan Mansyur sejak dirilisnya film Ada Apa Dengan Cinta 2. Karena katanya, puisi-puisi Rangga dalam film itu diambil dari karya Aan Mansyur. Saya sendiri belum nonton film itu.
Kemudian, saya membalik buku itu. Meneliti deret angka yang tertempel di pojok bawah sampulnya—sesuatu yang tak pernah saya lupa setiap akan membeli buku. Dan saya kaget seketika. Cantik itu Luka dihargai seratus ribu dikurangi satu rupiah. Ya, 99 ribu! Sejenak saya ragu, dan akhirnya meletakkan kembali novel itu ke tempatnya. Tidak. Tidak sekarang. Saya akan membeli buku ini, tapi tidak sekarang. Entah kapan. Semoga saja kelak buku ini masih ada dengan harga yang sudah lebih murah, atau ada versi e-booknya.
Begitu pula buku puisi milik Aan Mansyur. Harganya tak jauh beda dengan novel Eka Kurniawan tadi. Hanya selisih sedikit saja. Kembali, saya meletakkan buku itu di tempat semula.
♯
Tapi kemudian, mata saya tertuju pada dua buku yang terletak di deret rak yang sama. Mata saya berbinar lagi. Dua buku ini juga telah membuat saya penasaran sejak lama. Sama seperti dua buku sebelumnya, tak lupa saya menengok label harga yang tertera di sampul belakang. Hmm… delapanpuluh lima ribu dan limapuluh ribu.
Sejenak saya bimbang. Keempat buku ini sama-sama menerbitkan rasa penasaran saya. Saya ambil keempatnya sekaligus, atau bawa pulang dua saja dulu, ya? Ah, ini sungguh dilematis. Sekitar sepuluh menit saya berdiri di depan rak itu. Tak lepas memandangi keempat buku tadi. Hingga akhirnya saya memutuskan membawa dua buku saja ke meja kasir.
♯
Hingga sampai di ujung catatan ini, dua buku itu belum lepas dari bungkus plastiknya. Biarlah. Biar saja penasaran ini makin mengakar. Akan saya tuntaskan semuanya saat waktu sudah benar-benar luang.
♯
Hari ini, di Malang yang selalu mengguratkan banyak kenangan. Setelah melalui pergulatan dilema dan penasaran, akhirnya kubawa pulang dua karya itu.
Hari ini di kotaku tercinta, kukantongi “Sepotong Senja untuk Pacarku” yang dibawa oleh derasnya “Hujan Bulan Juni”.
Dua-duanya dituliskan dua lelaki berbeda, dengan nama depan yang sama-sama berawalan S.
Seno Gumira Ajidarma dan Sapardi Djoko Damono.
♯
23 Juli 2016
01:41 a.m
Adinda RD Kinasih
Cari Blog Ini
Terbaru
Baca Juga

Setiap Keberuntungan Punya Pemiliknya Masing-Masing
Juni 21, 2018

Bertemu Bandung (4.2)
Februari 19, 2020

Dua Garis Biru : Lebih dari Sekadar Seks Bebas
Juli 16, 2019

Perjalanan Berkisah 1 : Bali
Juli 10, 2022

Cerita Kedai Kopi (4) - Sade : Teh dan Kopi
Desember 17, 2020
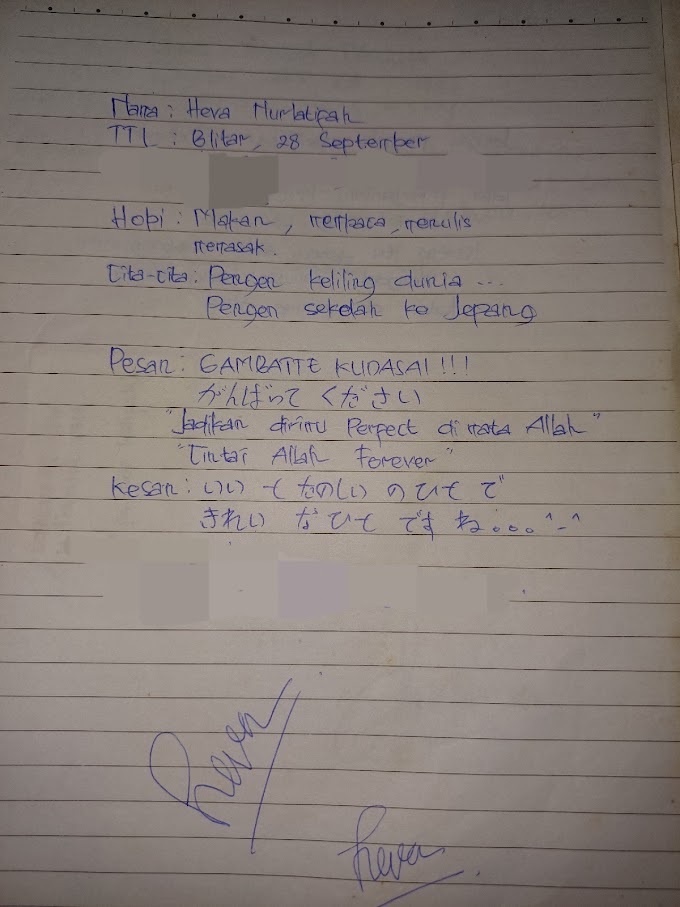
Cahaya Baik Itu Telah Pergi
Oktober 02, 2023
Designed with by Way2Themes | Distributed by Blogspot Themes





1 Komentar
Jadi penasaran Din .. pengen baca juga ..
BalasHapus